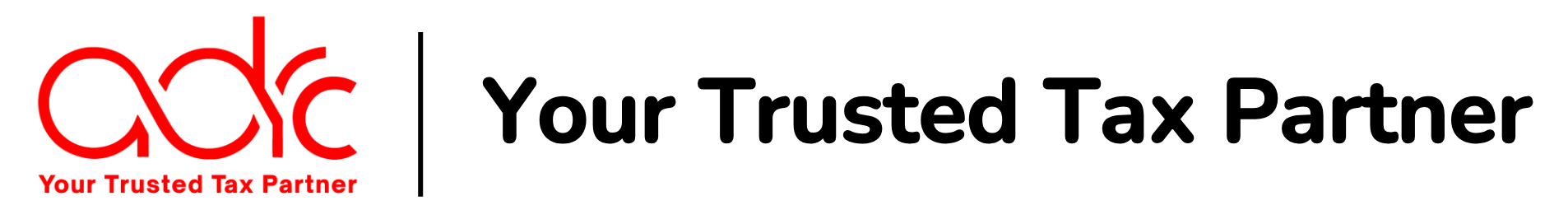JAKARTA – Beban berat menunggu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pasalnya jika shortfall melebar, target penerimaan pajak tahun depan akan semakin sulit dicapai, apalagi dengan hitungan normal, pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2026 menyentuh 13,5% atau dari outlook APBN 2025 sebesar Rp2.706,9 triliun ke angka Rp2.357,7 triliun.
Skenario Direktorat Jenderal Pajak alias DJP memang telah menyebut tentang kemungkinan pelebaran shortfall penerimaan pajak. Kalau merujuk Maklumat Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak (DJP) 6 Desember lalu, skenario untuk menjaga defisit APBN tidak melebihi 3% dari produk domestik bruto, penerimaan pajak minimal harus mencapai angka Rp2.005 triliun.
Artinya kalau penerimaan pajak berada di angka Rp2.005 triliun, maka target penerimaan pajak tahun depan bisa menembus angka 17,5%. Namun jika mengacu kepada nilai komitmen yang disampaikan para kepala kantor pajak dengan pejabat otoritas pajak saat rapat pimpinan di Bogor, Jawa Barat pada Oktober 2025 lalu yakni di angka Rp1.947,2 triliun, target pertumbuhannya bisa menembus angka 21,3%.
Target pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2026 cukup ambisius. Apalagi jika melihat kinerja penerimaan pajak hingga November 2025 yang masih terkontraksi sebesar 3,2% year on year. Penerimaan pajak yang masih terkontraksi di angka 3,2% itu jauh dari profil pertumbuhan alamiahnya. Seharusnya dengan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% dan inflasi di angka 2,5%, pertumbuhan penerimaan pajak idealnya berada di angka 8%.
Persoalannya, dalam catatan Bisnis, sangat jarang penerimaan pajak bisa melampaui pertumbuhan alamiahnya. Pada tahun 2024 misalnya, pertumbuhan penerimaan pajak hanya berada di angka 3,5%. Padahal pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% dan inflasi di angka 1,57%. Artinya pertumbuhan penerimaan pajak di angka 3,5% masih jauh di bawah profil pertumbuhan alamiahnya yang seharusnya bisa berada 6,6%.
Pemerintah sendiri berdalih bahwa kontraksi penerimaan pajak yang terjadi sepanjang Januari hingga November 2025 lalu, disebabkan oleh restitusi pajak yang cukup massif.
Sebagai perbandingan, nilai restitusi ini terlihat dari selisih pada pencatatan. Sampai dengan akhir November 2025 penerimaan pajak dibukukan sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari target. Sedangkan penerimaan bruto mencapai Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih mencapai Rp351 triliun. Selisih itu terjadi karena sejumlah hal, salah satunya restitusi pajak.
Besarnya porsi restitusi itu terjadi karena masuknya batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) dengan tarif 0%. Kondisi ini memicu massifnya restitusi, para pengusaha kena pajak (PKP) batu bara yang selalu untung tiap tahunnya, bisa mengklaim pajak masukan yang sudah keluar dari proses produksi hingga eksportasi ke otoritas pajak. Klaim itu bisa berwujud pengembalian pendahuluan atau restitusi. Restitusi diberikan setelah dilakukan pemeriksaan.
Meski menjadikan restitusi sebagai dalih melemahnya performa setoran pajak, namun data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipublikasikan pekan lalu, juga tidak bisa menutupi bahwa dihitung dengan penerimaan bruto sekalipun, kinerja penerimaan pajak masih jauh dari profil ekonominya. Pertumbuhan penerimaan pajak bruto hingga November 2025 hanya sebesar 1,9%, padahal seharusnya bisa di angka 8%.
Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya sejumlah kelemahan administrasi yang memicu setoran pajak tidak optimal. Lembaga auditor negara itu bahkan menyatakan bahwa Badan Kebijakan Fiskal yang kini telah berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Ditjen Pajak (DJP) belum menggunakan pertimbangan analisis tax gap dalam penyempurnaan regulasi pajak.
Menurut BPK, belum adanya pertimbangan analisis tax gap itu memicu tekanan yang cukup dalam penerimaan pajak. Hal itu dibuktikan dengan sulitnya rasio penerimaan pajak atau rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dari angka 8%. Regulasi perpajakan ini merupakan bagian dari policy gap.
Menariknya, salah satu temuan BPK menunjukkan bahwa DJEF tidak memiliki dokumen output formal berupa estimasi atau analisis tax gap. Mereka masih dalam tahap mempelajari metodologinya. Adapun versi Kemenkeu, estimasi tax gap pada 2024 tercatat sebesar 6% dari PDB dengan perincian policy gap 2,3% dan compliance gap sebesar 3,7%.
Revisi UU Cipta Kerja
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku tengah menghitung ulang dampak Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja terhadap anjloknya penerimaan negara akibat tingginya pengembalian pajak alias restitusi.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa restitusi adalah bagian dari hak wajib pajak (WP). Dia mengakui pengembalian yang tinggi terjadi di antaranya pada komoditas batu bara.
Komoditas ’emas hitam’ itu sebagian besar diekspor sehingga bebas dari PPN. Menurut Febrio, kondisi tersebut tidak lepas dari UU Cipta Kerja yang sudah berlaku selama empat tahun belakangan ini.
Hal tersebut juga sebelumnya sudah diakui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada saat rapat dengan Komisi XI DPR awal Desember 2025 ini.
“Ketika dia [batu bara] diekspor terjadi restitusi PPN-nya terutama, karena kan kalau barang ekspor kan tidak kena PPN. Nah, jadi itu restitusi menjadi cukup besar. Sekarang kami assess dampaknya, kami harus hitung ulang,” terang Febrio usai konferensi pers tersebut di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Minggu (21/12/2025).
Pejabat eselon I Kemenkeu itu pun mengakui rencana pengenaan bea keluar batu bara menjadi kebijakan yang diharapkan bisa membalikkan keadaan yang ada sekarang. Dengan memungut bea keluar, harapannya kondisi penerimaan negara dari sektor batu bara bisa kembali ke level sebelum UU Cipta Kerja.
“Ini makanya kami coba assess apakah bea keluar ini bisa membalikkan pendulumnya ke kondisi kurang lebih mirip seperti sebelum Undang-Undang Cipta Kerja,” tutur Febrio.
Secara lebih luas, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu menyebut pihaknya sedang melihat kembali prinsip keadilan dari industri-industri ekstraktif di Indonesia, tidak hanya batu bara. Prinsipnya mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Namun, dia memastikan pemerintah akan tetap memerhatikan aspek daya saing atau competitiveness dari industri di dalam negeri. “Jadi competitiveness untuk berbisnis sisi usaha tambang juga tetap kami perhatikan, tetapi keadilan sesuai dengan pasal 33 itu akan kami terus pegang,” ungkapnya.
Risiko Fiskal Semakin Terbuka
Risiko fiskal semakin terbuka jika penerimaan pajak pada tahun depan tidak sesuai ekspektasi. Perubahan struktural perlu dilakukan. Apalagi, tahun ini pemerintah telah menggunakan saldo lebih anggaran alias SAL untuk menambal defisit APBN.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti pemerintah agar penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup celah defisit tidak menjadi kebiasaan yang menggerus disiplin fiskal.
Adapun, Kementerian Keuangan menggunakan SAL sebesar Rp85,6 triliun sebagai bantalan pembiayaan APBN 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga defisit anggaran tetap sesuai outlook di level 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan langkah tersebut merupakan langkah sah pragmatis untuk menahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baru di tengah ketidakpastian global. Hanya saja, dia mengingatkan adanya risiko “ilusi ruang fiskal” apabila strategi ini terus dijadikan sandaran.
“Defisit yang tampak terkendali secara angka bisa menyembunyikan masalah struktural jika ditopang oleh pengurasan cadangan,” kata Rizal kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).
Rizal mengingatkan bahwa penggunaan SAL dalam jumlah signifikan mencerminkan tekanan nyata pada sisi penerimaan negara, sementara belanja pemerintah bersifat kaku (rigid). Jika ‘tabungan’ negara itu terlalu sering dipakai untuk menutup celah pembiayaan rutin maka fungsi utama SAL sebagai peredam kejut (shock absorber) akan hilang. Akibatnya, ruang gerak pemerintah akan menyempit ketika terjadi guncangan ekonomi eksternal yang lebih besar.
“Risiko lainnya adalah munculnya preseden fiskal yang keliru, di mana stabilitas defisit dijaga lebih melalui optimalisasi kas daripada melalui penguatan kualitas APBN itu sendiri,” lanjutnya.
Menurut Rizal, ketergantungan pada SAL berpotensi melemahkan disiplin fiskal jangka menengah karena pemerintah bisa saja menunda reformasi fundamental, seperti perbaikan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) dan efisiensi belanja.
Oleh karena itu, Indef mendesak pemerintah untuk menetapkan ‘aturan main’ yang jelas terkait penggunaan sisa anggaran tersebut. Idealnya, menurut Rizal, SAL hanya boleh ditarik untuk menutup guncangan penerimaan yang bersifat sementara (temporary shock), bukan untuk membiayai belanja rutin.
“Pemerintah perlu memastikan penggunaan SAL bersifat selektif. Harus ada batas minimum SAL yang dijaga agar tidak menciptakan ilusi ruang fiskal yang semu,” pungkasnya.
———————-
Artikel berjudul “Shortfall Pajak Bakal Melebar, Target Purbaya Tahun Depan Sulit Dikejar
“ dikutip dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20251222/259/1938633/shortfall-pajak-bakal-melebar-target-purbaya-tahun-depan-sulit-dikejar